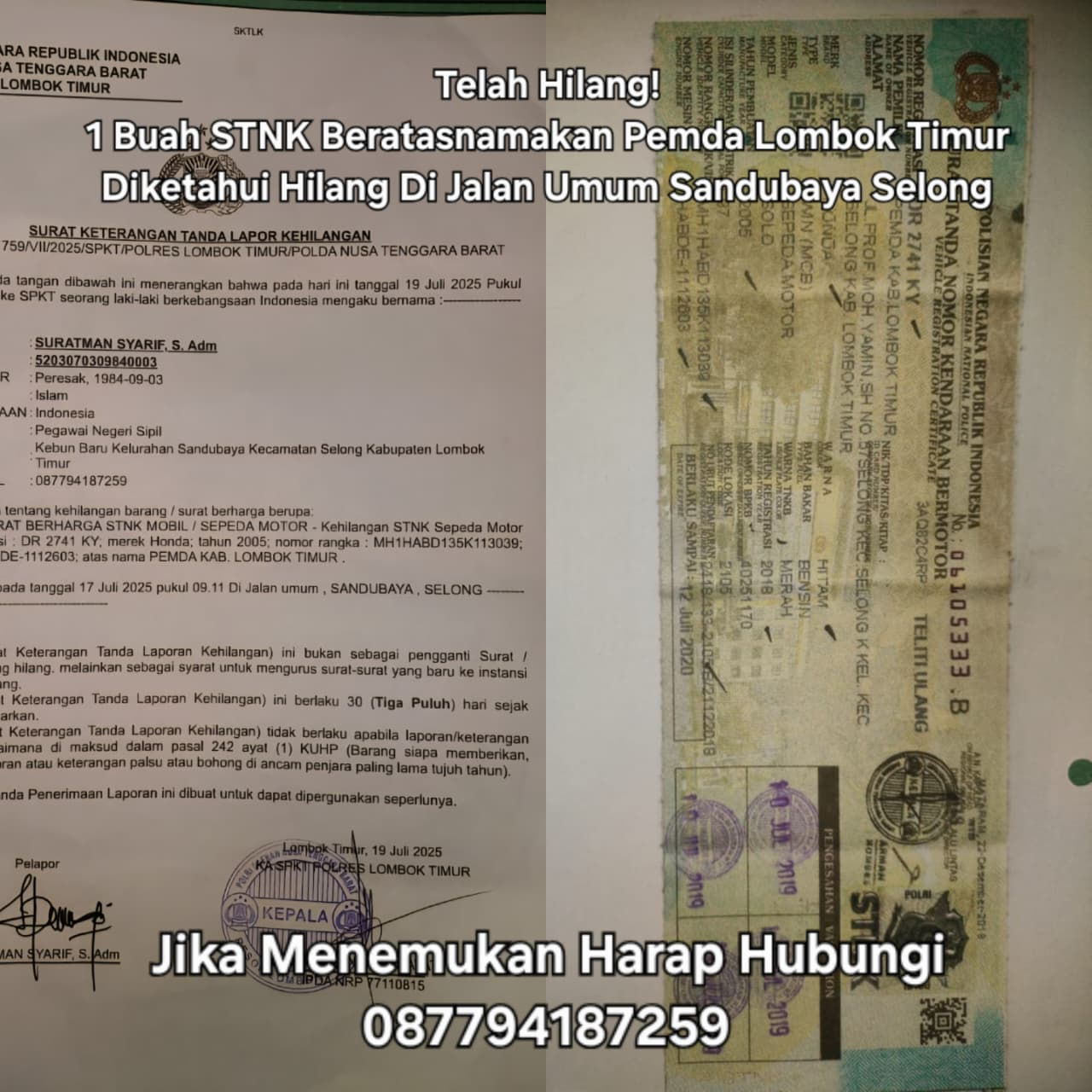Pohuwato dan Harga Mahal Sebuah Investasi: Ketika Kebenaran Berdiri Sendirian Melawan Kuasa
POHUWATO – “Orang benar akan terlihat salah jika dia sendirian. Orang yang salah akan terlihat benar jika dia berkelompok.”
Kalimat yang ditulis Kepala Desa Hoho itu bukan sekadar status media sosial. Ia adalah potret telanjang tentang wajah dunia hari ini, tentang bagaimana kebenaran kerap dikalahkan oleh kekuasaan, dan nurani ditenggelamkan oleh kepentingan yang dibungkus rapi atas nama investasi dan pembangunan.
Di Pohuwato, kalimat itu bukan teori. Ia hidup, bernapas, dan melukai kesadaran masyarakat setiap hari.
Saya adalah anak cucu penambang Pohuwato. Leluhur kami telah lama hidup berdampingan dengan alam. Menambang bukanlah tindakan rakus, melainkan cara bertahan hidup yang diwariskan dengan nilai keseimbangan. Alam dihormati, tanah dijaga, dan kehidupan dilangsungkan tanpa keserakahan. Ada etika, ada batas, ada kesadaran bahwa alam bukan untuk dihabiskan, melainkan dirawat.
Namun hari ini, wajah pertambangan telah menjelma menjadi mesin raksasa yang dingin dan rakus. Ketika perusahaan-perusahaan besar datang membawa jargon investasi, pembangunan, dan kesejahteraan, kenyataan di lapangan justru berkata lain. Hutan ditebang tanpa ampun, tanah dikuliti hingga tak bernyawa, bukit diratakan, dan sungai dipaksa menelan limbah. Semua berjalan cepat, sistematis, dan berizin, namun keadilan justru tertinggal jauh.
Yang paling menyayat nurani adalah ketika ruang-ruang paling sakral dalam kehidupan ikut dikorbankan. Di belakang sekolah yang dahulu hijau oleh pepohonan, tempat anak-anak belajar dan menanam harapan, kini hanya tersisa tanah gundul dan debu. Pemandangan itu adalah simbol nyata: keuntungan mampu mengalahkan pendidikan, masa depan, dan keselamatan generasi.
Dalam konflik antara masyarakat dan korporasi tambang, kebenaran sering diposisikan sebagai ancaman. Warga yang mempertahankan tanahnya dicap anti-pembangunan. Mereka yang bertanya tentang AMDAL, reklamasi, dan tanggung jawab lingkungan disebut pengganggu stabilitas. Suara kritis dilemahkan, dipinggirkan, bahkan dibungkam, seolah hak atas lingkungan yang sehat bukan hak dasar warga negara.
Di sinilah ketidakadilan sosial berdiri dengan pongah. Ketika masyarakat kecil berdiri sendiri, kebenaran tampak rapuh dan mudah disalahkan. Sebaliknya, kesalahan yang dilakukan secara berkelompok, oleh korporasi besar, dilindungi regulasi yang timpang dan relasi kuasa, tampak sah, normal, bahkan kebal hukum. Orang benar terlihat salah karena ia sendirian. Orang salah terlihat benar karena ia ramai dan berkuasa.
Pembangunan yang mengorbankan manusia dan lingkungan bukanlah kemajuan. Ia adalah kemunduran yang dipoles dengan istilah investasi. Kekayaan alam Pohuwato seharusnya menjadi berkah bagi rakyatnya, bukan berubah menjadi sumber konflik, ketakutan, dan kemiskinan struktural. Ketika tanah dirampas, hutan hilang, dan ruang hidup menyempit, yang direnggut bukan hanya ekonomi rakyat, tetapi juga martabat manusia.
Dunia memang tidak selalu adil. Namun ketidakadilan tidak boleh diterima sebagai takdir. Tetap menjadi orang benar meski sendirian adalah pilihan moral yang mahal, tetapi itulah satu-satunya jalan agar sejarah tidak mencatat kita sebagai generasi yang diam ketika tanahnya dilukai.
Pohuwato bukan sekadar peta konsesi, bukan angka produksi, dan bukan target investasi. Ia adalah rumah, ladang, sekolah, sungai, dan masa depan anak-anak kami. Jika hari ini kita memilih diam demi kenyamanan sesaat, maka anak cucu kita kelak hanya akan mewarisi lubang-lubang tambang dan kisah tentang keberanian yang seharusnya pernah ada.
Biarlah suara ini kecil dan sering sendirian. Karena kebenaran tidak pernah membutuhkan kerumunan untuk tetap menjadi benar. Ia hanya membutuhkan keberanian, untuk berdiri tegak, bersuara lantang, dan terus melawan arus, meski berhadapan langsung dengan kekuasaan.
(Penulis: Yopi Y. Latif, C.ILJ)
(Jurnalis: Rey)